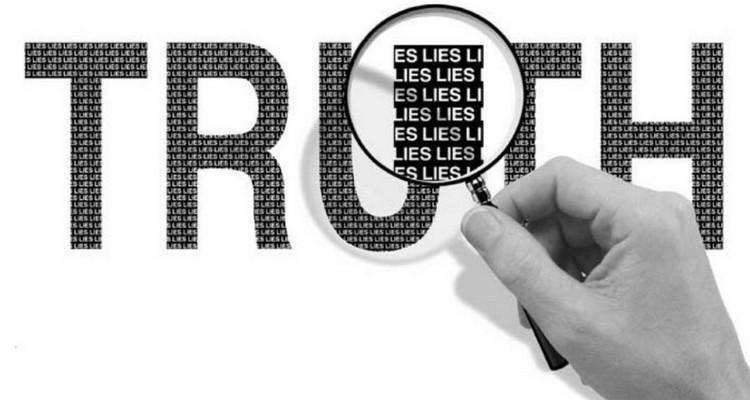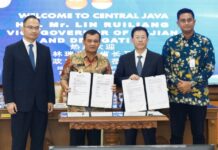Semarang, Idola 92.6 FM – Drama Ratna Sarumpaet yang dikonstruksi media sosial dan kemudian diambil media arus utama akhirnya berhenti. Ujung cerita berakhir dengan anti-klimaks. Ibarat pepatah Jawa, becik ketitik ala ketara. Sepandai-pandai bangkai disembunyikan pada akhirnya juga kan tercium juga.
Kita bersyukur, kebohongan itu telah layu sebelum berkembang. Kita jadi bertanya-tanya—apa jadinya jika kebohongan itu tidak segera terungkap—lalu diamplifikasi sedemikian rupa sehingga kemudian dipersepsi sebagai kebenaran dan menimbulkan dampak politik yang sistemik. Oleh karena itu, kekonyolan, kebohongan dan kehebohan yang melingkupi kasus ini hendaknya menjadi pijakan untuk menangani kasus serupa di kemudian hari.
Dari sepenggal episode kisah muram Ratna Sarumpaet bisa dikatakan. Inilah era post-truth atau paska kebenaran. Kebenaran bukan ditentukan oleh data dan fakta melainkan oleh keyakinan. Ketika ada fakta di media sosial yang sejalan dengan keyakinan maka diyakinilah kebenaran fakta itu. Inilah awal kematian akal sehat. Dalam kasus Ratna Sarumpaet, media sosial telah dijadikan sampah kebohongan. Jejak digital para politisi tak bisa dihapus dan akan terus diingat masyarakat.
Lantas, bagaimana mengarusutamakan literasi digital di era post-truth, belajar pada kasus kebohongan Ratna Sarumpaet? Apa sesungguhnya pokok persoalan masih terus munculnya kabar bohong? Benarkah ini akan semakin tumbuh subur jelang Pemilu 2019? Bagaimana segenap komponen bangsa menangkalnya?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Devie Rahmawati (Pengamat Sosial dari Universitas Indonesia) dan Prof Syamsuddin Haris (Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI). [Heri CS]
Berikut diskusinya: