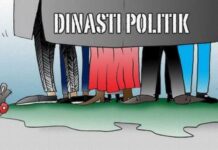Semarang, Idola 92.6 FM – Plato pernah berkata: “The price good men pay for indifference to public affairs…is to be ruled by evil men.” – Harga yang harus dibayar oleh orang baik atas ketidakpedulian mereka terhadap urusan publik adalah diperintah oleh orang jahat.
Jejaring dinasti politik Hasan Aminuddin terbentang sejak 18 tahun silam. Setelah ia dua kali terpilih sebagai bupati Probolinggo, pucuk pimpinan kabupaten di Jawa Timur itu kemudian seolah “dialihkan” ke istrinya—Puput Tantriana Sari, yang juga menjabat dua periode.
Dinasti dibangun dengan memaksa birokrasi loyal dan meredam suara kritis dari masyarakat. Pada akhirnya, ambisi Hasan Aminuddin yang juga anggota DPR dari Fraksi Nasdem dan Bupati Puput untuk melanggengkan ambisi dinasti politik tersandung operasi tangkap tangan KPK.
Fenomena kepala daerah yang tertangkap KPK karena korupsi kerap mewarnai dinamika perjalanan Pilkada langsung selama ini. KPK mencatat ada 429 kepala daerah hasil Pilkada yang terjerat kasus korupsi per 18 Maret 2021 lalu. Sebelum Bupati Probolinggo, kita ingat, tiga bulan lalu ada Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, kemudian sebelumnya Bupati Klaten Sri Hartini.
Meski tidak selalu, akan tetapi secara empiris, politik dinasti sering menjadi pintu bagi praktik korupsi dan aksi balik modal. Maka, agar fenomena ini tak terus terulang, seperti kata Plato—agar publik tidak dipimpin oleh orang jahat, bagaimana membatasinya? Perlukah dinasti politik dibatasi? Sudahkah ada aturan dan perundang-undangan yang membatasinya?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Prof Siti Zuhro (peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI); Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Peneliti Senior di Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit)/ Mantan Anggota KPU RI); dan Agus Riewanto (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta). (her/ yes/ ao)
Dengarkan podcast diskusinya: